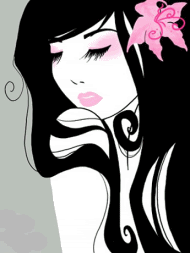Seorang gadis termenung di depan
jendela kamar, menatapi bulan sabit yang muncul malu-malu di balik awan.
Hembusan angin malam menerpa wajahnya dengan lembut. Hamparan padi yang
terletak di belakang rumah mulai terlihat menguning meski di tengah gelapnya
malam. Pepohonan berayun-ayun diterpa angin, seakan mengajaknya menari. Dia
menghela napas panjang, sibuk dengan pikirannya sendiri. Besok, dia harus
pindah dari desa dan meninggalkan semua pemandangan indah ini.
Ayahnya, Joko Kirsan, memutuskan
untuk tinggal di Jakarta dengan harapan memperbaiki ekonomi keluarga. Beberapa
hari lalu, rumahnya dibakar. Mereka mengambil tanahnya untuk membangun tempat
wisata. Mereka tidak memberi ganti rugi, hanya memberi sejumlah uang yang tidak
akan pernah bisa menggantikan rumah yang lama. Bukan karna rumahnya dulu adalah
sebuah rumah yang besar. Tapi dia membangun rumah itu dengan tangannya sendiri.
Satu-satunya adikarya yang pernah dia punya. Pernikahannya jelas sekali bukan
adikarya. Istrinya bodoh, mereka bahkan tidak tahu cara berkomunikasi. Mereka tidak
pernah bersekolah.
Berbeda dengan Komar, yang
mati-matian disekolahkannya agar menjadi sebuah adikarya.
Hari pertama di sekolah baru, Komar
gugup sekali dan bisa merasakan detak jantungnya yang berdebar lebih cepat. Tak
ada satupun yang dia kenal disini, dan mereka juga tidak peduli dengan
kehadirannya. Ditemani Bu Dwi, dia masuk ke kelasnya dan sangat takjub ketika
melihat kelas yang luas dengan jumlah murid terbatas, papan tulis berwana
putih, lantai ubin yang jarang ditemuinya dan meja putih tanpa coretan
sedikitpun yang sangat berbeda dengan keadaan sekolahnya di desa yang berlantai
tanah liat, meja reyot dan papan tulis kapur, membuat siapapun batuk-batuk
kalau duduk di barisan depan. Lamunannya terpecah ketika diminta memperkenalkan
diri di depan teman-temannya oleh Bu Dwi.
Komar ke depan dan tersenyum manis.
“Halo teman-teman. Nama saya Komariah…”
“Hahahaha… namanya kampungan!”
sahut salah satu murid laki-laki sambil menunjuk wajah Komar dengan geli yang
langsung ditegur oleh Bu Dwi. Seketika, murid seisi kelas pun ikut menertawakan
Komar. Belum selesai memperkenalkan diri, Komariah kembali duduk di kursinya
dengan rasa kesal dan mata berkaca-kaca, dia bisa merasakan panas di wajahnya
karena malu. Murid-murid masih memerhatikannya dengan pandangan aneh dan
menahan tawa. Komar bertanya-tanya di dalam hati apa yang salah dari dirinya,
namun dia tetap berusaha untuk tenang dan bersabar, bersabar menunggu bel
pulang sekolah berbunyi.
Jakarta pada siang hari sangatlah
terik. Apalagi angkot yang ditumpanginya penuh sesak. Komar bergegas mengganti
seragam sekolah untuk membantu ayahnya mencari sesuap nasi guna membiayai
anggota keluarganya dengan berjualan bubur di pinggir jalan depan gang rumah
mereka hingga sore dan pulang ke rumah untuk beristirahat dengan mendorong
gerobak yang masih menyisakan banyak porsi bubur ayam.
Pagi hari ketika Komar terbangun
dari tidurnya, dia teringat desanya yang dulu. Desa yang tidak mengenal
kemacetan dan kebisingan. Desa yang air sungainya mengalir jernih dan
pepohonannya rindang membuat Komar malas untuk pergi ke sekolah, ditambah
dengan perilaku temannya yang menjengkelkan tidak seperti teman-temannya di
desa dulu. Namun, dia tetap bergegas mempersiapkan diri untuk bersekolah, lalu
berjalan sambil menunggu angkot yang lewat setelah berpamitan dengan ayah yang
sangat menyayanginya.
Di sekolah, ketika Komar berjalan
menuju kursinya, dia terkejut mendengar ejekan tentang ayahnya. “Komar anak
jokbur, Komar anak Joko tukang bubur”. Entah dari mana mereka tahu bahwa ayah
Komar adalah penjual bubur. Tapi Komar acuh dan pergi meninggalkan teman-teman
yang mengejeknya.
Hal yang sama terjadi berulang kali,
mereka terus-menerus melecehkan pekerjaan Joko. Komar tidak tahan lagi dan
mengadu pada ayahnya sambil menangis. “Pak, Komar mau pindah sekolah ke kampung
saja, pak”.
“Mengapa kamu mau pindah?” tanya
Joko.
“Saya nggak kuat di sekolahan
diejek melulu, pak” jawab Komar.
Seminggu sebelum mengikuti ujian,
Komar bahkan meminta ayahnya agar ke sekolah. Maksudnya agar Joko menegur
teman-teman yang kerap mengejeknya. Dengan meminjam sepeda, Joko segera ke
sekolah Komar. Setibanya di sekolah, Joko malah bingung apa yang harus
disampaikan pada teman-teman Komar. Akhirnya, Joko mencoba meyakinkan Komar untuk
bersabar dan mengatakan bahwa menjual bubur adalah pekerjaan yang halal.
“Sudah, kamu ikut tes saja dulu”
ujar Joko.
Dalam hati, Joko sudah bertekad
akan memindahkan Komar ke sekolah di desa neneknya, di Jawa Tengah sesudah
ujian nanti.
Di rumah, ketika Komar sendirian di
kamar dan hanya bisa mengingat ledekan teman-temannya, dia melihat kabel
televisi yang tidak terpakai lagi. “Kabel ini cantik juga jika dililitkan di
leherku” pikirnya. Satu, dua, tiga.
Segalanya terasa seperti gerakan
lambat. Satu-satunya adikarya Joko yang tersisa, dia melayang, mungkin karna
badannya terlalu ringan.